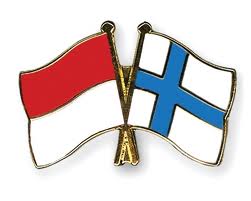Pendidikan Sebelum Kemerdekaan
A.Sejarah
Dalam arti luas, sejarah merupakan
catatan tentang apa yang diucapkan, dilakukan, dialami atau dirasakan oleh
manusia. Segala peristiwa yang dialami manusia akan dicatat, kapan terjadinya,
di mana peristiwa terjadi serta siapa pelakunya merupakan unsure penting dalam
sejarah.
Dalam pengembangan sejarah manusia,
waktu dan tempat memiliki arti sangat penting. Sebab dalam menyusun sejarah
kita harus tahu siapa pelakunya, kapan dan di mana peristiwanya.
B. Pendidikan
sebelum Masa Kolonial
1.
Sejarah Pendidikan pada Zaman Hindu-Budha
Masuknya kebudayaan Hindu di beberapa daerah di pulau
Jawa menjadi titik awal zaman sejarah tulis menulis di Indonesia. Tulisan
dengan huruf Pallawa yang berisi sastra, agama, sejarah, etika menjadi sumber
pendidikan golongan raja-raja dan bangsawan. Pendidikan mengharuskan anak-anak,
pemuda dan orang dewasa mempelajari huruf Pallawa. Zaman pemerintahan Erlangga
(990-1049) banyak buku-buku bahasa, sastra, hukum, filsafat diterjemahkan ke
bahasa Jawa kuno (Kawi) sehingga lahirlah guru-guru profesional pada zamannya.
Seorang guru profesional harus lahir dari kasta Brahmana sedang muridnya bisa
terdiri dari kasta Brahmana sendiri sandar 2 kasta di bawahnya, sebab kasta
sudra tidak diperkenankan menjadi murid.
56Puncak pendidikan Budha dicapai pada zaman
Sriwijaya. Guru terkenal pada zaman Sriwijaya ialah Darmapala dari Nalanda.
Tahun 685, I Tsing (seorang Budhis Cina) yang pulang dari India singgah di
Sriwijaya menerjemahkan 100 buku agama Budha ke dalam bahasa Cina. Bermula dari
hal ini, agama Budha banyak dipelajari orang-orang sehingga akhirnya Budha
berkembang di pulau Jawa.
2. Sejarah
Pendidikan pada Zaman Kerajaan Islam
Pada
abad ke-13 Islam masuk ke Indonesia. Kerajaan Islam pertama di Jawa ialah Demak,
di Aceh Samudra Pasai, di Sulawesi kerajaan Goa dengan Raja Goa Alaudin dan di
daerah Maluku Kesultanan Ternate. Dari kerajaan-kerajaan itulah menjadi pusat
penyebaran agama Islam sehingga Islam tersebar ke seluruh nusantara. Bermula
dari penyebaran Islam di dalamnya inklusif pendidikan bercorak Islam
tradisional dikembangkan. Sebagai pusat perkembangan Islam, para kiai
mendirikan pondok pesantren. Dalam pondok pesantren itu para kiai hidup bersama
santri memperdalam agama Islam.
Penyelenggaraan
pendidikan agama Islam masih bersifat perorangan. Para kiai membina umat Islam
di daerahnya masing-masing dengan mendirikan pondok pesantren. Terkenallah
peran Walisanga di Jawa, para syeh Minangkabau dan pada akhirnya berdiri
kesultanan-kesultanan sebagai pusat pemerintahan dan pusat penyebaran Islam.
Tujuan
pendidikan Islam pada saat itu adalah mengabdi sepenuhnya kepada Allah sesuai
dengan tuntunan rasul Muhammad SAW ( Al Qur’an dan Sunah). Materi
pendidikan yang diberikan para kiai adalah keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq.
Untuk memperdalam ilmu tauhid diberikan juga Arkanul Iman.
Untuk
mencapai tujuan tersebut diberikan program belajar yang meliputi:
- 1. membaca Al Qur’an;
- 2. ibadat (berwudlu, shalat);
- 3. keimanan;
- 4. akhla
- Cara belajar saat itu adalah dengan model sorogan dan klasikal. Model sorogan atau individual dilakukan dengan anak santri duduk bersila berhadapan dengan guru gaji untuk membaca Al Qur’an, secara bergantian satu persatu sesuai dengan kemajuannya masing-masing. Demikian pula dalam hal belajar berwudlu, salat seorang santri dibimbing langsung oleh guru. Pendidikan akhlaq diberikan secara klasikal, guru bercerita tentang tarikh nabi, Sabat nabi, sifat-sifat terpuji atau yang tercela dengan materi para tokoh pada zamannya. Lama belajar tidak ditentukan, sangat bergantung pada kemampuan, kerajinan dan kemauan anak. Karena itu belajar tidak dipungut biaya. Hal ini berlangsung sampai masuknya kebudayaan barat.
C.
Pendidikan pada Masa Kolonial

Tahun
1596, di bawah pimpinan Cornelis Ed Houtman, Belanda pertama kalinya datang ke
Indonesia. Misi kedatangannya adalah berdagang. Dengan menyusuri pantai Jawa,
Belanda akhirnya mencapai daerah Timur (Ambon dan sekitarnya). Mereka kembali
dengan membawa rempah-rempah yang cukup banyak. Sejak saat itu pedagang Belanda
yang datang ke Indonesia semakin ramai. Untuk menghindari persaingan, tahun
1602 Belanda mendirikan VOC (Persatuan Dagang Hindia Timur). Dengan dalih
perdagangan inilah, VOC terus memperkuat perdagangannya. Lewat politik yang
dilakukannya dengan raja-raja Jawa, VOC sebagai kepanjangan tangan Belanda
akhirnya menjadikan Indonesia sebagai daerah jajahan (koloni).
Untuk lebih
memperkuat kedudukan, Belanda mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak
Indonesia. Sekolah ini bertujuan menghasilkan pegawai-pegawai rendahan baik
untuk pegawai negeri maupun pegawai swasta. Pembukaan sekolah itu didorong oleh
kebutuhan praktis berkaitan dengan pekerjaan di berbagai bidang dan kejuruan.
Secara umum kecenderungan penyelenggaraan pendidikan kolonial adalah sebagai
berikut:
1. Membiarkan
terselenggaranya pendidikan Islam tradisional serta membantu mendirikan
beberapa madrasah Islamiah di Nusantara misalnya:
Melanjutkan sistem lama dalam bentuk
pengajian Al-qur’an dan Kitab Kuning.
2. Mendirikan
pondok pesantren modern misalnya di Jombang Ponpes Tebuireng, di Ponorogo
Ponpes Gontor.
3. Mendirikan sekolah agama atau
madrasah misalnya madrasah adabiah di Aceh, Madrasah maktab Islamiah di
Tapanuli medan.
4. Mendirikan
sekolah Zending (misionaris) yang bertujuan menyebarkan agama
Kristen untuk orang-orang Belanda dan buni putra. Beberapa sekolah yang
didirikan Belanda misalnya:
a.
1607 mendirikan sekolah di Ambon
dengan bahasa Melayu dan Belanda.
b.
1622 mendirikan sekolah di Kepulauan
Banda lengkap dengan asrama.
c.
1630 mendirikan sekolah Warga
Masyarakat di Jakarta untuk tingkat sekolah dasar yang mendidik budi pekerti.
d.
16422 mendirikan sekolah latin
(tingkat SMP) di Jakarta.
e.
1745 mendirikan Seminari Theologika
untuk mendidik calon pendeta.
f.
1817 mendirikan sekolah dasar Eropa,
untuk penduduk Eropa (semua orang Belanda, semua orang yang asalnya dari Eropa,
semua orang Jepang). Sekolah dasar ini terus berkembang, pada tahun 1902
menjadi 173 buah.
g.
1860 mendirikan Gymnasium
(sekolah lanjutan) Willem III, merupakan sekolah lanjutan tingkat pertama untuk
orang Eropa di Batavia.
h.
1848 atas keputusan Raja mendirikan
20 sekolah dasar Bumiputera di setiap Karesidenan Jawa.
i.
1892 sekolah dasar dibagti menjadi
dua kategori, yaitu: sekolah dasar Kelas Pertama ( de schoolen der
eerste klasse) untuk golongan Bumiputera (bangsawan & penduduk yang
kaya) dan sekolah dasar Kelas Dua (de schoolen der tweede klasse) untuk
Bumiputera umum.
j.
1856 mendirikan sekolah guru (kweeksschool)
di Surakarta, 1874 di Ambon, 1875 di Probolinggo, 1875 di Banjarmasin, 1876 di
Makassar, 1879 di Padang Sidempuan.k. 1851 mendirikan sekolah dokter Jawa
dengan lama pendidikan 2 tahun setelah sekolah rakyat 5 tahun.Dari
sekolah-sekolah yang didirikan Belanda dapat dilihat beberapa ciri khas, antara
lain:
a)
dualistik diskriminatif, yaitu untuk
membedakan pendidikan untuk orang Eropa dan Bumiputera.
b)
Sentralistik yaitu pemerintah
kolonial Belanda memiliki hak mengatur pendidikan di daerah koloninya.
c)
Tujuannya untuk dapat menghasilkan
tamatan yang menjadi warga negara Belanda kelas dua.
D.Pendidikan
pada Masa Pergerakan

Pergerakan nasional lahir karena
penderitaan rakyat. Bangsa Indonesia tertinggal di berbagai bidang, termasuk
pendidikan. Sebagian rakyat buta huruf, karena tidak semua orang bisa masuk sekolah.
Dalam keadaan seperti itu, golongan pelajar yang mendapat kesempatan masuk ke
jenjang sekolah yang lebih tinggi saat itu tampil untuk mempelopori dan
memimpin pergerakan nasional. Termasuk pendiri Taman Siswa, Raden
Mas Soewardi Soeryaningrat atau yang
biasa dikenal dengan Ki Hajar Dewantara.
Taman
Siswa berdiri pada 3 Juli 1922. Taman
Siswa merupakan badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat melalui
pendidikan untuk mencapai tujuan perjuangan, yaitu mewujudkan manusia Indonesia
yang merdeka lahir dan batinnya.
Pendidikan Taman Siswa dilaksanakan berdasarkan Sistem
Tutwuri Handayani (jika di belakang memberi dorongan), di manasistem ini
berorientasi pendidikan pada anak didik. Artinya pelaksanaan pendidikan lebih
didasarkan pada minat dan potensi apa yang perlu dikembangkan pada anak didik.
Dalam sistem ini berlaku sistem kekeluargaan, yang artinya diharuskan bagi
setiap pendidik untuk meluangkan waktu 24 jam setiap harinya untuk memberikan
pelayanan kepada anak didik, sebagaimana orang tua yang memberikan pelayanan
kepada anaknya.
Untuk mencapai tujuan
pendidikannya, Taman Siswa menyelanggarakan kerja sama yang selaras antar tiga
pusat pendidikan yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan
lingkungan masyarakat. Pusat pendidikan yang satu dengan yang lain hendaknya
saling berkoordinasi dan saling mengisi kekurangan yang ada. Penerapan sistem
pendidikan seperti ini yang dinamakan Sistem Trisentra Pendidikan atau Sistem
Tripusat Pendidikan.
Pendidikan Taman Siswa
berciri khas Pancadarma, yaitu:
·
Kodrat Alam (memperhatikan sunatullah)
·
Kebudayaan (menerapkan teori Trikon; Kontinyu, Konvergen, dan
Konsentris)
·
Kemerdekaan (memperhatikan potensi dan minat maing-masing
individu dan kelompok),
·
Kebangsaan (berorientasi pada keutuhan bangsa dengan berbagai
ragam suku),
·
dan Kemanusiaan (menjunjung harkat dan martabat setiap orang).
E. Pendidikan
pada Masa Jepang

Pendidikan zaman jepang disebut
“Hakko Ichiu”, yakni mengajak bangsa Indonesia bekerja sama dalam rangka
mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang sangat dipengaruhi motif
untuk mendukung kemenangan militer Jepang dalam peperangan Pasifik.
Jepang
menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas
terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Hal-hal tersebut antara
lain:
1. Dijadikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi
pengantar pendidikan menggantikan Bahasa Belanda
2. Adanya integrasi sistem pendidikan dengan
dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan
Belanda.
Adapun susunan pengajaran menjadi, pertama, Sekolah
Rakyat enam tahun (termasuk sekolah pertama). Kedua, sekolah menengah tiga
tahun. Ketiga, sekolah menengah tinggi tiga tahun (SMA pada zaman Jepang)
Tujuan pendidikan pada zaman Jepang
tidak hanya memenangkan peperangan. Secara konkret tujuan yang ingin dicapai
Jepang adalah menyediakan tenaga cuma-cuma (rumosha) dan prajurit-prajurit yang
membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Oleh karena itu, para pelajar diharuskan
mengikuti latihan fisik, kemiliteran dan indoktrinasi ketat. Sekolah-sekolah yang bertipe akademis
diganti dengan sekolah-sekolah yang bertipe vokasi. Jepang juga melarang pihak
swasta mendirikan sekolah lanjutan dan untuk kepentingan kontrol.Kebijakan ini
menyebabkan terjadinya kemunduran yang luar biasa bagi dunia pendidikan dilihat
dari aspek kelembagaan dan operasonalisasi pendidikan lainnya
Pada masa pendudukannya, Jepang tidak begitu menghiraukan kepentingan
agama, yang penting bagi mereka adalah keperluan untuk memenangkan perang. Ada
satu hal istimewa dalam pendidikan jepang sebagaimana telah dikemukakan, yaitu
sekolah-sekolah telah diseragamkan dan dinegerikan meskipun sekolah-sekolah
swasta lain diizinkan terus berkembang dengan pengaturan dan diselenggarakan
oleh pendudukan Jepang.
Sementara itu perkembangan
pendidikan Islam pada masa ini berkembang dengan pesat. Pendidikan Islam
mencoba memadukan antara pendidikan modern Belanda dengan pendidikan
tradisional sehingga melahirkan madrasah-madarasah berkelas yang tidak hanya
memberikan pengetahuan agama saja akan tetapi juga memberikan pengetahuan umum.
Untuk mempercepat usaha Jepang dalam
mencapai tujuan mereka, segala cara ditempuh dalam segala segi kehidupan. Salah
satunya dengan mengubah sistem pendidikan. Oleh sebab itu, Jepang menguasai
kurikulum baru, yang berlaku secara umum untuk semua sekolah. Dalam kurikulum
ini bahasa Indonesia menjadi pelajaran utama, bahasa Jepang menjadi pelajaran
wajib. Para pelajar harus mempelajari adat istiadat Jepang, taiso, melagukan
lagu Jepang, melakukan penghormatan (selkerei) ke arah istana kaisar Tokyo.
Guru-guru juga harus dilatih agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang
dibebankan Jepang. Selain itu, diberikan pelajaran tentang dasar-dasar
pertahanan dan kemiliteran.
Walaupun
demikian, ada beberapa segi positif
sistem pendidikan pada zaman penjajahan Jepang bagi rakyat Indonesia,
yaitu:
Ø Jepang
memerikan pendidikan militer kepada para pemuda Indonesia.
Ø Menghapus
dualisme pendidikan penjajahan belanda dan nenggantinya dengan dengan
pendidikan yang sama bagi setiap orang.
Ø Pemakaian
bahasa Indonesia secara luas diinstruksikan oleh penjajah Jepang.
BAB III
PENUTUP
Dengan mengetahui sistem-sistem pendidikan sebelum kemerdekaan kita dapat membedakan sistem pendidikan pada zaman hindu-budha, zaman kerajaan islam, masa kolonial, masa pergerakan dan masa pendudukan jepang. Kita dapat menjadikan sejarah pendidikan di Indonesia sebagai suatu bahan pembelajaran untuk masa depan yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu juga sebagai pengalaman yang paling berbekas untuk membentuk kepribadian setiap individu penuntut ilmu,agar lebih giat belajar mengenai kesalahan-kesalahan bangsa terdahulu. Sehingga bangsa kita dapat lebih unggul dari bangsa-bangsa lainnya melalui pendidikan. Karena pendidikan merupakan salah satu tolak ukur kemajuan satu bangsa